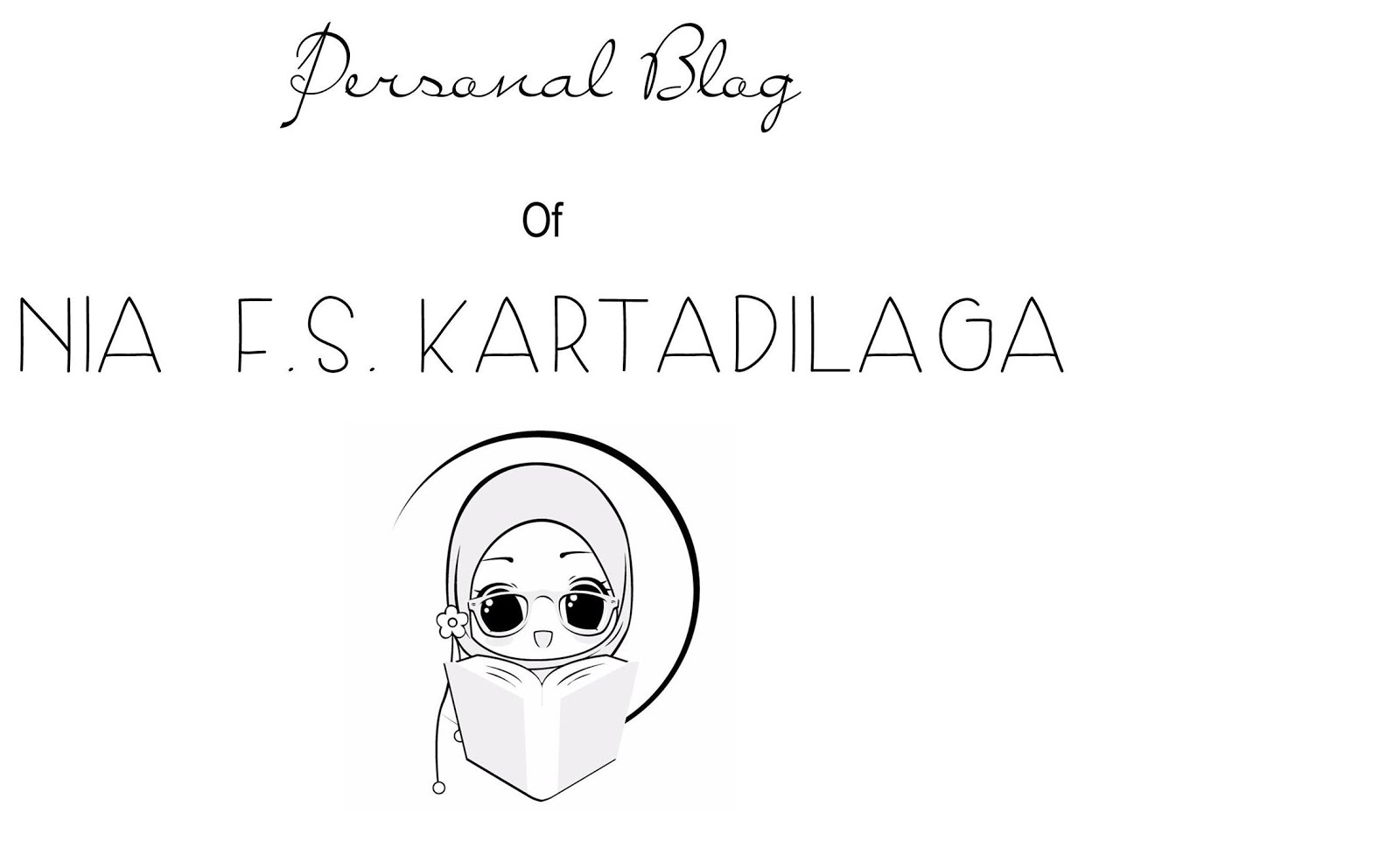Minggu depan. Jangan lupa, ya. Kita ketemu di reuni akbar. Dateng lho. Jangan sampe enggak. Oke?!
Aku menatap pesan singkat darinya, orang yang selama ini masih terus berusaha menjaga hubungannya denganku, seberapa keras pun aku berusaha mengenyahkannya.
Tidak. Aku benar-benar tidak ingin menghadiri acara apapun yang berpotensi membuatku harus kembali mengenang kejadian-kejadian lama, kejadian yang membuatku ingin menghilang selamanya dari dunia. Menghilang.
***
"Kamu yakin?"
Aku menatap mata bulat itu, mata yang selalu memancarkan semangat dan juga jenaka, "Yakin, dong. Aku kalau enggak yakin, enggak akan dateng ke kamu sekarang..."
"Iya sih... Tapi, kamu kan tahu kalau ini bukan hal yang biasa kamu lakukan."
"Kamu enggak percaya sama kemampuan aku?" Aku merasa sedang mengalami penolakan. Terus terang saja, aku merasa sedikit tersinggung meskipun aku tahu apa yang sebenarnya sedang berusaha dia lakukan; menjagaku.
"Bukan itu. Bukan..."
"Iya... Aku paham kok. Aku ngerti banget maksud kamu apa. Tapi gini aja deh... Aku janji akan berusaha menjaga diri aku dengan baik. Aku janji akan lakukan persiapan banyak, masih ada sebulan kan sebelum kita berangkat? Aku janji akan jaga kesehatan."
Dan dia, terdiam.
"Aku enggak akan maksa naik gunung, janji!"
Dia, masih terdiam.
"Kita cari rute hiking yang paling ringan, kamu pasti tahu kan di mana?"
"Fisik kamu..."
"Kamu menghina fisik aku? Kamu anggap aku benar-benar lemah?"
Kali ini, aku yang memilih diam.
***
Sudah H-3. Aku tunggu kamu dateng lho. Jangan sampe enggak, ya. Pleaseee... Ini sudah 5 tahun kamu memilih untuk enggak pernah dateng di acara reuni kita. Mau sampe kapan?
Belum selesai aku membaca, muncul lagi pesan baru darinya.
Aku tahu, sangat tahu. Tapi, aku pikir sudah saatnya kamu berhenti begini. Aku nanti jemput kamu dan kali ini, aku tidak menerima penolakan. Oke?
Napasku, terasa semakin berat.
***
"Papa sama Mama kamu, benar kasih izin?"
"Kamu pikir aku bohong?"
"Bukan... Bukan gitu. Yaa, aku kan sering dengar kamu bilang kalau kamu paling dilarang untuk ikut aktivitas outdoor. Wajar kalau aku memastikan dulu, kan?"
"Sudah deh. Aku tahu kamu enggak percaya sama aku!"
Aku merapikan buku-buku di atas meja dengan tergesa. Rasanya ingin sekali menangis. Kenapa susah sekali meyakinkan laki-laki kesayanganku ini bahwa aku mampu. Ini memang akan aktivitas outdoor pertamaku. I mean, di luar aktivitas olahraga ringan yang biasa aku lakukan di sekolah atau jogging setiap pagi. Aku tahu Papa dan Mama melarangku, susah payah aku akhirnya diizinkan.
"Sana! Hari ini aku mau pulang sendiri!" Dengan kasar aku berlari meninggalkannya dan membanting pintu kelas. Tidak peduli bahwa kami menjadi tontonan gratis bagi yang lain.
Dia berlari mengejarku, memegang tanganku, "Enggak gitu, aku percaya. Iya, aku percaya. Aku cuma mau memastikan aja. Enggak lebih. Jangan marah, ya. Kita pulang bareng, sekalian aku nanti tanya langsung ke Mama kamu. Oke?"
***
Pertemuan terakhir kami.
Kalau saja aku menyadari bahwa pertengkaran tersebut akan menjadi pertengkaran terakhir kami selamanya, mungkin aku tidak akan pernah memilih bertengkar.
Kalau saja waktu itu aku lebih memahami bahwa dia selalu bermaksud baik terhadapku, selalu khawatir dengan keselamatanku dibandingkan keselamatannya sendiri, aku pasti tidak akan pernah memaksakan kehendak.
Kalau saja.
Andai saja itu bukan pertemuan terakhir kami.
Aku meremas kaus yang sedang kupakai. Aku melempar benda-benda di atas meja kamar, yang terjangkau oleh tanganku. Aku lempar semuanya hingga melihat salah satu foto kenangan kami berdua ikut terlempar dan mendarat dengan sukses di kakiku.
Ini foto terakhir kami.
Aku menangis, meraung, dan menjerit. Entah apa saja yang sudah aku lakukan hingga Papa mendobrak pintu kamar dan Mama masuk dengan wajah penuh khawatir. Wajah mereka, wajah khawatir dan sedih, wajah yang selalu memancarkan kesan yang sama selama lima tahun terakhir.
Lima tahun. Terakhir.
Mama memelukku, mengusap punggungku, pelan... "Ada apa?"
Suara ini, selama lima tahun terakhir ini, tidak pernah sekalipun Papa dan Mama berkata kepadaku dengan suara selain suara penuh kelembutan sekaligus kesedihan mendalam. Aku baru menyadarinya.
"Nak..." Kali ini Papa yang maju, mengusap kepalaku, "Ikhlaskan..."
Bagaimana bisa aku mengikhlaskan?
Alih-alih mengatakannya langsung ke Papa, aku justru semakin menangis. Terus, menangis.
***
Besok, ya. Aku jemput kamu. Aku mau kamu dateng di acara reuni akbar angkatan kita.
Aku, menekan tombol delete.