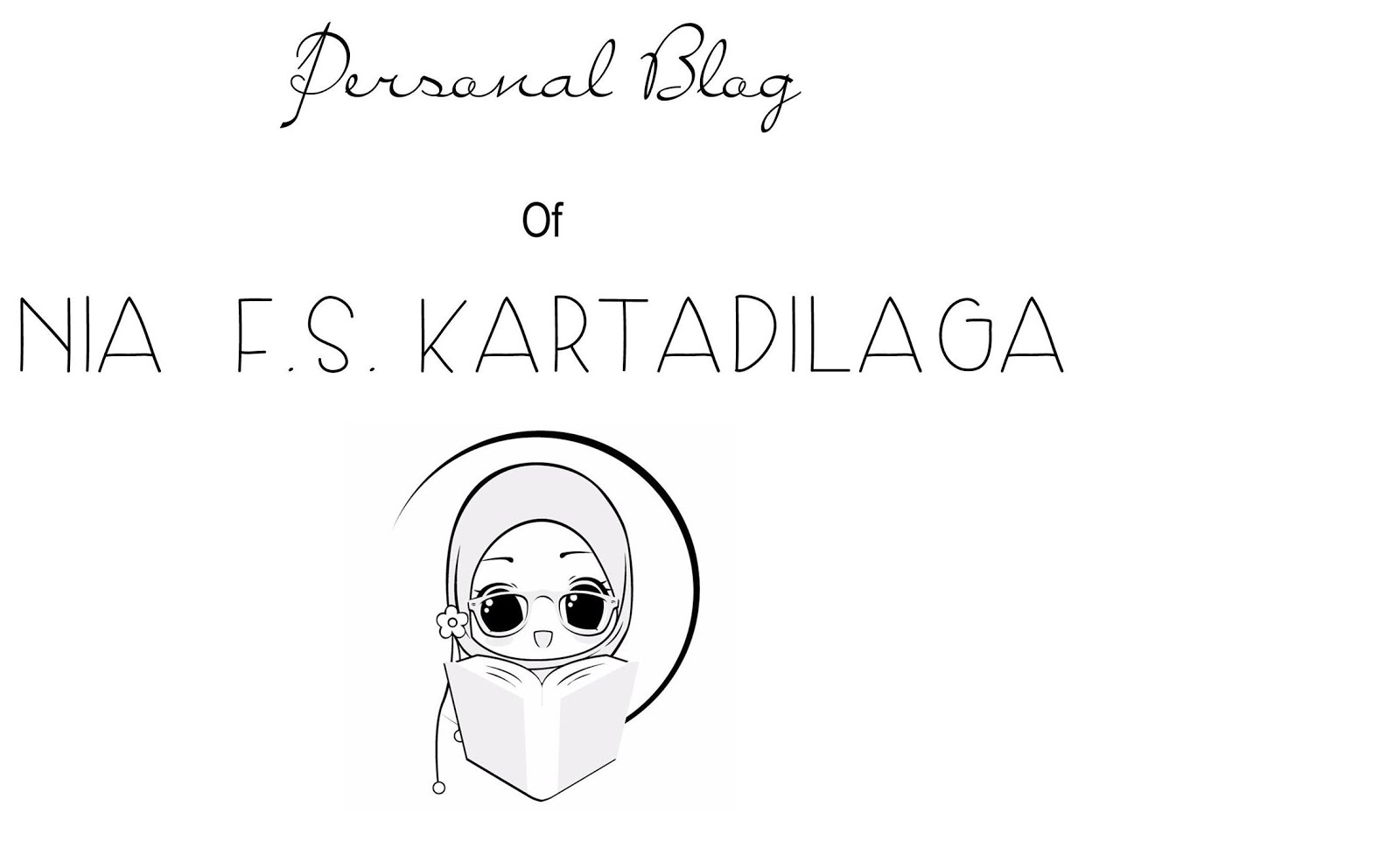Masih ingat dengan kasus bullying yang menyebabkan kematian dua orang siswa di SMA Negeri 3 Jakarta baru-baru ini? Kesamaan nama sekolah dengan SMA saya membuat saya teringat dengan apa saja yang saya alami selama SMA dan perbandingannya dengan yang saya alami selama kuliah. Dalam hal ini, fokus utama yang akan saya bahas terkait dengan senioritas yang berujung pada bullyingyang dianggap “halal”.
Masa Orientasi Siswa (MOS) SMA bukan lagi sekadar perkenalan biasa seperti yang saya alami di SD-SMP, tetapi merambah kepada aktivitas berbau senioritas dan perploncoan. Hal ini membuat saya sampai berpikir bahwa “kegiatan marah-marah” merupakan hal yang “wajar” dilakukan oleh “kakak kelas” terhadap “adik kelas” atas nama “solidaritas” dan “pendidikan”.
Sebelumnya saya tidak pernah berpikir bahwa untuk menjadi “peserta MOS terbaik”, saya harus dimarahi dan dibentak-bentak oleh panita. Itu pengalaman pertama saya dibawa ke sebuah ruangan khusus; “ruang eksekusi”. Saya dibentak sampai ludah panitia-panitia yang membentak muncrat ke kening dan wajah saya, saya gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki karena shock dan menahan marah. Ada yang sampai hendak melempari saya dengan pot bunga. Sepanjang MOS saya berusaha menutupi bahwa saya adalah anak dari salah satu guru senior demi beberapa alasan -- hanya kakak ruang yang tahu karena saya sempat lupa membawa baju seragam dan Ibu yang mengantarkan baju tersebut ke sekolah dengan menitipkan melalui kakak ruang saya. Tetapi, pengalaman tidak menyenangkan tersebut membuat saya bertekad; kalau sampai saya mengalami kekerasan fisik lanjutan, maka saya tidak akan diam dan membongkar siapa saya sekaligus memperkarakan perbuatan mereka. Sederhana saja, saya tidak pernah mengalami kekerasan seperti itu dari orang tua, jadi tidak mungkin saya akan membiarkan orang lain melakukannya terhadap saya.
Setelah MOS, pengalaman terkait dengan senioritas seperti itu saya alami ketika menjalani masa-masa orientasi di beberapa organisasi yang saya ikuti. Selama masa re-organisasi, junior pasti akan di-diklat oleh senior. Ada masa di mana kami harus dididik dan dilatih, bukan hanya terkait pengetahuan melainkan juga ketahanan fisik. Hukuman fisik, seperti scotch-jump dan push-up, merupakan “hukuman biasa”. Begitu juga merayap di sungai ketika kami menjalani diklat di salah satu perkebunan kelapa sawit yang ada di Lampung. Terakhir yang saya dengar, diklat di perkebunan tersebut sudah dihapus. Tidak seperti beberapa teman yang menyayangkan penghapusan tersebut, saya justru mendukungnya. Apalagi, ketika saya kuliah, saya menjalani proses orientasi sebagai mahasiswa baru yang jauh lebih mendidik. Jadi, saya merasa bahwa pendidikan dan masa perkenalan memang sudah sewajarnya jauh dari kata “penyiksaan” yang tidak tepat sasaran, bahkan berpotensi berujung pada kematian.
Saya diterima di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saat saya menjadi mahasiswa baru, masa-masa itu merupakan masa-masa heboh dengan berita kematian praja STPDN (sekarang IPDN) bernama Wahyu. Mau tidak mau, saya kembali teringat dengan masa-masa yang saya lalui ketika SMA dan membandingkan dengan yang saya alami ketika kuliah. Selama SMA, fakta bahwa saya adalah anak dari salah satu guru senior yang memiliki image “guru baik”, membuat saya banyak “selamat” dari aktivitas perploncoan yang tidak wajar. Kedekatan dengan beberapa kakak kelas yang menjadi panitia-panitia inti dari kegiatan tersebut juga membuat saya “selamat”. Tidak seperti beberapa teman (laki-laki maupun perempuan) yang bercerita kepada saya bahwa mereka sampai ditampar.
Selama ospek, saya "mengumpulkan" kesalahan hingga 13 buah selama 2 hari. Saat peserta yang memiliki kesalahan harus dibawa ke “ruang hukuman”, saya sudah pasrah jika harus mengalami proses seperti saat SMA. Ditambah saya tidak memiliki backinglagi seperti saat SMA. Ternyata, yang saya alami jauh dari sifat “melecehkan”.
Hari pertama, saya diminta merenungkan kesalahan dan memikirkan hukuman yang “pantas”. Saat itu, saya memilih dihukum scotch-jump atau push-up. Begitu mendengar hukuman yang saya pilih, senior yang menangani saya justru tertawa. Mereka berkata, “Kami tidak menerima hukuman fisik”. Hasil akhirnya, saya hanya diminta membaca puisi dengan tema sesuai kesalahan yang saya buat. Itupun dibacakan di depan para senior yang menangani saya saja, bukan di ruang publik. Hari kedua, lebih enak lagi. Saya yang mengantuk parah, diberi hukuman berupa tidur dan baru boleh bangun ketika diberi aba-aba harus berpura-pura sedang mengalami mimpi buruk. Ini dilakukan secara massalbersama teman-teman lainnya, yang dikumpulkan di ruangan khusus dengan lampu dimatikan. Siapa yang menolak tidur pada situasi seperti itu? Hahaha...
Tugas-tugas yang diberikan selama ospek kuliah juga jauh dari kata “tidak berguna”. Tugas kami adalah membuat esai dan dinilai. Persis seperti guru/dosen memberi nilai terhadap tugas kita! Selama sebulan selanjutnya, kami bukan hanya berkutat dengan esai tetapi juga dengan makalah kelompok maupun laporan individu. Sangat sinergis dengan kehidupan perkuliahan yang sarat dengan tugas-tugas sejenis. “Pemanasan” yang dialami selama ospek sangat membantu proses adaptasi ketika menjalani kuliah.
Semenjak itu, saya semakin menyadari bahwa ada yang salah dengan sistem ospek yang berkembang luas di Indonesia dan ada yang salah dengan konsep senioritas. Konsep yang berkembang melahirkan posisi superior vs inferior.
 |
| Ilustrasi gambar diperoleh dari sini. |
Tidak mengherankan ketika senior merasa superior, maka junior “harus” tunduk menjadi kubu inferior. Konsep inilah, yang saya pelajari, menjadi akar dari kasus-kasus bullying karena tidak ada kesetaraan posisi antara senior dan junior. Berbeda dengan yang saya alami ketika kuliah, di mana nyaris tidak ada gap antara senior-junior. Jarang sekali senior yang mau dipanggil “Kak”, “Mas”, atau “Mbak” karena sebutan “Mas” dan “Mbak” lebih berlaku untuk dosen, karyawan, hingga cleaning service serta untuk memperkecil gap.
Pengalaman menjadi pelaku bullyingketika TK juga membuat saya merasa “takut” dengan kasus-kasus bullying sekarang. Anak usia early childhood bisa "membunuh" temannya karena bullying.
Ketika kuliah saya belajar tentang bullying melalui pengalaman langsung dan materi-materi serta studi kasus yang diberikan. Hal tersebut yang membuat saya memiliki konsep bahwa sekolah impian bukan hanya yang memaksimalkan fungsi perpustakaan sekolah, melainkan yang juga jauh dari senioritas dan bullying tanpa batas. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan pihak-pihak yang bersedia mengubah pola “salah” yang sudah terbentuk. Baik panitia dan guru/dosen harus saling membantu serta mendukung proses perubahan tersebut. Karena semua berawal dari bagaimana kita memulai, maka melakukan program yang tepat saat MOS sekolah dan ospek universitas adalah kunci pertama untuk memulai proses yang anti-bullying dan anti-senioritas salah kaprah. Minimal, contohlah program ospek yang saya jalani ketika masuk kuliah dulu; tugas atau aktivitas yang diberikan oleh panitia kepada peserta, sinergis dengan yang akan dihadapi saat aktivitas belajar-mengajar berjalan.
 |
| Have a blessed day! |
Mommylicious #ParentingBook