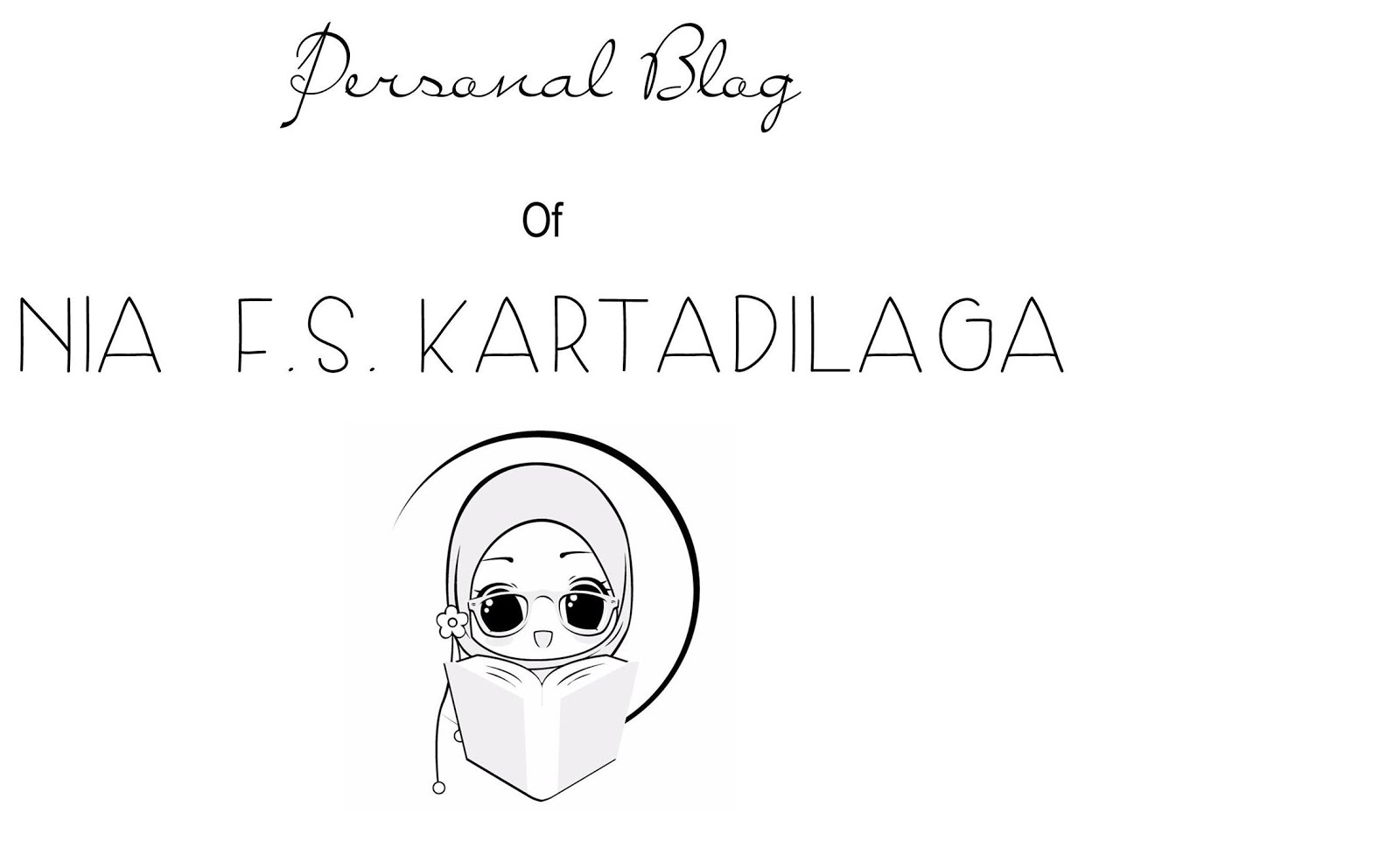Karya Ahmad Zaki Fauzi yang diikutsertakan di #SGANia November.
Ribuan debit hujan menghunjam bumi Jakarta. Pecahan-pecahannya umpama serpihan intan. Indah namun dingin dan menyakitkan. Aku berlari sembari menyembunyikan lembaran kertas dalam dekapanku. Tujuanku saat ini hanya satu; berteduh.
Gerombol hujan masih terdengar mengerikan di permukaan kanopi di sebuah gerai fotokopi tempatku berteduh. Mereka mengetuk-ngetuk seolah ingin merobek apa pun yang menghalangi tujuan mereka sampai ke tanah. Tidak banyak orang lain yang berani lalu lalang tanpa memakai payung maupun jas hujan. Hujan siang ini terlalu deras.
Di sini, di tempatku berdiri, hanya ada dua orang petugas gerai yang masih sibuk mengurusi fotokopi pesanan pelanggan dan sepasang mahasiswa kampus yang juga berteduh.
Kudekap lebih erat lembaran kertas yang masih tersisa. Seolah hari ini bernasib sial, lima belas koran ibu kota masih di tanganku dan bertambah sial lagi ketika aku mendapati ujung-ujung beberapa koranku basah terciprat air kecokelatan.
“Seharusnya nggak berlari terlalu keras,” gumamku lirih meratapi koran demek ini terciprat-ciprat ketika berlari tadi.
Bola mataku beralih ke gadis berjilbab modis, perempuan yang berdiri di samping kekasihnya itu ternyata tengah mengamatiku. Kedua matanya yang indah nan lentik mendadak berputar ke arah lain, diikuti wajahnya yang berpaling dari menatapku, seolah-olah aku ini sampah yang menjijikkan.
Dia ramping, tinggi, cantik, sepadan dengan lelaki necis yang diapit lengannya olehnya. Ada yang salah dengan diriku, aku merunduk tersadar betapa mengerikannya diriku. Kotor. Kumuh. Kusam. Dekil. Bau. Tidak sama seperti mereka. Dengan derajat di tingkat paling rendah dalam berpenampilan, aku memang seperti itu.
Hujan mulai reda namun langit siang ini masih dinaungi bergulung-gulung awan hitam. Pekat dan gelap, seakan waktu berputar cepat menjelang magrib. Sepasang mahasiswa tadi sudah meninggalkan tempat ini, dengan sebelumnya, lagi-lagi gadis itu menoleh ke arahku, mencibirku meski tanpa suara.
Kini jalan di depan gerai fotokopi kembali dipadati motor dan orang-orang yang berlalu lalang. Setelah hujan reda, aktivitas kembali seperti sedia kala. Tukang rujak buah kembali mengelap etalase buahnya. Ibu penjual pecel keliling merapikan dagangannya, kemudian mengangkat nampannya kembali ke atas kepala.
Titik-titik hujan seperti kapas sudah tidak terasa lagi ketika aku merentangkan telapak tanganku ke langit. Mudah-mudahan, benar-benar reda. Aku merapikan lembaran-lembaran koran itu, menyusunnya kembali, meski kotor di ujung-ujungnya tidak bisa kusembunyikan. Bagiku, setiap lembar kertas ini adalah receh. Pekerjaan ini selaksa tempat memupuk mimpi dan harapan untuk mengumpulkan barang seratus dua ratus keping uang. Jauh lebih bermanfaat daripada mengamen dengan tubuh penuh tindik dan rambut sepotong punuk kuda yang membuat penumpang di dalam mobil diliputi ketakutan. Mungkin hasil dari mengamen lebih menjanjikan, namun menjual koran membuatku betah berlama-lama mencari berkah. Ibu yang mengajarkanku tentang keberkahan.
Aku memasukkan uang kembali ke dalam saku. Baru terkumpul delapan belas ribu lima ratus, dipakai untuk makan di warteg saja sudah habis, jika pun tersisa mungkin tinggal lima ribu. Lima ribu mana cukup untuk membeli obat ibu. Obat warung yang khasiatnya itu-itu saja tidak banyak membantu meski harganya lebih murah.
“Ibu muntah darah?” tanyaku sembari menggenggam salah satu lengan ibu, saat itu dua hari yang lalu.
Ibu menggeleng. “Cuma batuk biasa,” lanjutnya lalu meraih air putih dan meminumnya. Ia kembali bersandar di tumpukan bantal di atas kasur.
Mata ibu kembali menerawang, meratapi kesendiriannya yang malang lantaran suami jarang sekali pulang. Sekali pulang, ada saja yang diributkan. Mulai dari hal kecil sampai hal besar.
“Ibu mau cerita, mungkin ini dongeng yang tidak pernah ibu uraikan. Dahulu, sepasang kekasih mengikrarkan janji untuk sehidup semati. Keduanya jatuh hati karena memiliki hobi yang sama, kemiripan yang sama. Mereka hobi membuat busur lengkap dengan panah. Si wanita menikmati setiap detik belajar memanah bersama si pria. Si pria pun merasakan hal yang sama. Dua tahun menikah, buah hati mereka lahir, anak laki-laki yang menggemaskan,” ibu menghela napas, kubiarkan jeda yang cukup lama di sana. “Janji sehidup semati kandas. Si pria tidak betah berlama-lama hidup dengan kondisi kurang berkecukupan. Pria itu memilih mengadu nasib dengan berjudi. Lupa waktu. Lupa istri. Lupa anak. Mencampakkan semuanya.”
Aku memilih memijit kedua betis ibu, alih-alih penasaran mendengarkan dongeng selanjutnya aku memilih terdiam. Seolah menangkap sesuatu yang menarik, kedua mataku menatap sebuah busur dan panah menggantung di dinding kamar. Itu panah kami, panah yang dahulu pernah ayah ajarkan untuk berburu kelinci hutan saat kami masih tinggal di kampung. Aku masih ingat, meski saat itu berusia tiga tahun jalan.
“Anak laki-laki mereka tumbuh dengan ceria, meski hidup dalam keluarga yang kurang berkecukupan. Tidak seperti teman-temannya yang bebas jajan es dan menikmati gulali.”
“Bu,” aku menginterupsi, aku merasa kehidupan anak laki-laki itu tidak jauh berbeda dengan kehidupanku. “Anak laki-laki itu sama seperti kitaya, maksud aku sama sepertiku?”
Ibu mengangguk lemah.“Persis. Seumuran. Mereka seperti anak kembar.”
“Siapa namanya, bu?” aku tak sabar, siapa tahu setelah mengetahui hal ini aku mendapatkan teman yang senasib serupa seperuntungan.
“Danuh.”
Saat itu, kepalaku pusing. Dunia seakan berputar. Ini bukan dongeng. “Itu namanya sejarah, bu. Sejarah tentang aku. Aku ‘kan sudah mau naik kelas enam, kata kakak kelasku yang udah duduk di SMP, nanti di sana kita belajar sejarah.”
Ibu tersenyum mendengarkan celotehku, seolah-olah aku ini komidi kuda mini yang tengah berputar, yang membuatnya melupakan kesedihan-kesedihannya.
“Kenapa harus Danuh, bu?”
“Saat ibu memanggil Danuh, ibu merasa jiwa sagitarius —pemanah— berada di dalam nama itu. Mungkin karena sebuah nama begitu berarti sehingga saat kita menjadi orang tua, kita akan memilih nama yang baik untuk anak kita. Nama yang akan membuat kita terkenang saat memanggil dirinya.”
“Nama yang bagus, bu. Ibu pasti membela mati-matian saat nama itu diberikan kepadaku.”
“Ya. Karena saat itu ayahmu ingin nama kamu Antonio,” ibu terkekeh lalu terbatuk-batuk kecil. “Makan dengan sambal terasi pakai nama Antonio, mbok ya ndak pas rasanya.”
Aku ikut terkikik juga membayangkannya. Geli sendiri. “Danuh, bu. Nama anak itu sekarang, Danuh.”
“Ya, Danuh.”
Aku tersadar ketika salah satu petugas gerai fotokopi mengusirku, katanya kehadiranku berdiri di sini membawa sial, menjadikan pelanggan enggan memfotokopi tugas-tugas mereka karena jijik kepadaku. Sebegitunya ‘kah?
Baru lima langkah aku meninggalkan gerai fotokopi, tiba-tiba terdengar suara lelaki dewasa menyebut-nyebut namaku. Kupikir aku masih berada dalam dunia imajiku bersama ibu, namun ternyata lelaki itu mendekat ke arahku. Napasnya menderu, bahunya mengguncang karena letih mencari-cariku.
Aku mundur satu langkah, mengambil ancang-ancang seandainya ia bersiap menyakitiku lagi. Ya, lagi, bukan hanya sekali dua kali, namun lebih dari lima kali. Untuk satu dan ribuan alasan lain, aku tidak mau menceritakan hal ini kepada siapa pun.
“Tenang,” lelaki itu berbisik, pelan namun terdengar jelas. “Danuh, pulanglah. Sudah kubunuh ibumu dengan panah kesayangan kita. Agar kamu tidak usah lagi mencari seperak dua perak untuk biaya berobat ibu, Nak.”
Begitulah ayah, sudah kubilang, untuk satu dan ribuan alasan lain aku begitu membencinya.[]
Rabu, 10 Desember 2014
21:43 WIB
Cisauk, Tangerang